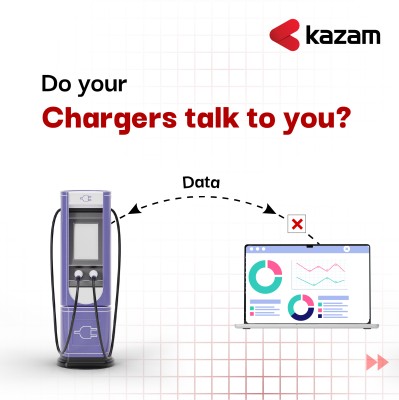Pulau Kemaro pernah menjadi lokasi benteng maritim Kesultanan Palembang pada awal abad ke-19, berkat lokasinya yang kering dan strategis.
Palembang, Sumatra Selatan (Xinhua/Indonesia Window) – Pulau Kemaro, sebuah pulau kecil di
Sungai Musi di Provinsi Sumatra Selatan, telah menjadi bagian penting dalam sejarah kebudayaan Palembang sejak abad ke-17. Melalui legenda cinta antara Siti Fatimah dan Tan Bun An, pulau ini merekam jejak awal pertemuan masyarakat lokal dan etnis Tionghoa. Pagoda yang menjulang, kelenteng tua, serta tradisi perayaan Cap Go Meh menjadi penanda kuat akulturasi yang masih terasa hingga kini. Lebih dari sekadar tempat bersejarah, Pulau Kemaro adalah simbol keberagaman yang saling mengakar.
Asal-usul legenda Pulau KemaroDi tengah derasnya arus Sungai Musi, berdiri sebuah delta kecil berjuluk Pulau Kemaro yang letaknya sekitar 6 kilometer dari pusat Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan. Berasal dari kata ‘kemarau’, nama ‘Kemaro’ sendiri diberikan karena konon pulau ini tidak pernah tenggelam meskipun Sungai Musi meluap saat musim hujan.
Pulau ini juga pernah menjadi lokasi benteng maritim Kesultanan Palembang pada awal abad ke-19, berkat lokasinya yang kering dan strategis. Pulau Kemaro terkenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kisah cinta tragis yang menjadi legenda turun-temurun.
Alkisah, Pulau Kemaro berawal dari kisah tragis antara Siti Fatimah, putri kerajaan Palembang, dan Tan Bun An, saudagar muda dari China. Mereka jatuh cinta saat Tan Bun An datang ke Palembang untuk berdagang. Ketika hendak menikah, Tan Bun An mengajak Siti Fatimah ke China untuk bertemu dengan orang tua Tan Bun An. Ketika pamit pulang, keluarga Tan Bun An menghadiahi tujuh guci berisi emas sebagai mahar, tetapi emas tersebut disembunyikan menggunakan sawi asin agar tidak dicuri.
Sesampainya di perairan Sungai Musi, Tan Bun An membuka guci-guci tersebut. Betapa terkejutnya dia saat menemukan bahwa isinya hanyalah sawi asin. Tanpa berpikir panjang dan tenggelam dalam amarah, dia membuang guci-guci itu ke sungai karena mengira isinya hanya sawi. Namun, guci terakhir terjatuh dan pecah di atas perahu layar. Ternyata, di dalam guci tersebut tersimpan emas.
Seketika Tan Bun An langsung melompat ke sungai untuk mencari emas-emas tersebut, diikuti oleh seorang pengawal yang membantunya. Setelah beberapa lama, keduanya tak kunjung muncul, sehingga Siti Fatimah pun ikut melompat untuk menolong. Namun, ketiganya tidak pernah terlihat kembali.
Menurut legenda, tak lama setelah kejadian itu, muncul sebuah daratan kecil di tempat mereka tenggelam. Daratan tersebut sekarang dikenal sebagai Pulau Kemaro. Di pulau itu, terdapat makam sederhana yang dipercaya sebagai tempat terakhir keduanya. Kisah ini menjadi simbol cinta sejati yang melampaui perbedaan budaya dan menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Tionghoa di Palembang.
Warisan budaya Tionghoa di Pulau KemaroDi Pulau Kemaro terdapat sejumlah bangunan utama yang menjadi jejak penting warisan budaya Tionghoa di Palembang, di antaranya sebuah pagoda, kelenteng, makam leluhur, dan pohon cinta (Tree of Love). Keempatnya menjadi simbol kuat
hubungan historis antara komunitas Tionghoa dan masyarakat lokal. Bangunan-bangunan ini tidak hanya memiliki nilai arsitektur dan sejarah, tetapi juga masih aktif digunakan dalam kegiatan keagamaan dan budaya dari 1968 hingga sekarang.
Salah satu bangunan yang paling mencolok dan menjadi ikon pulau ini adalah pagoda yang terletak di bagian tengah pulau. Dibangun pada 2006, pagoda tersebut memiliki tinggi 45 meter dan terdiri dari sembilan tingkat, dengan masing-masing tingkat setinggi 5 meter. Desain pagoda ini dirancang mengikuti prinsip Feng Shui, yang mencerminkan keharmonisan antara manusia dan alam.
Selain struktur fisiknya yang megah, bentuk segi delapan pada pagoda ini juga menyimpan makna budaya yang mendalam. Dalam kepercayaan Tionghoa, bentuk segi delapan melambangkan delapan arah energi yang dikenal sebagai Pat Kawa (Ba Gua).
Warna-warna cerah, seperti merah, emas, dan hijau, yang menghiasi bangunan ini bukan hanya untuk keindahan semata, melainkan juga sarat makna. Warna-warna tersebut memiliki makna perlindungan, kebahagiaan, dan harapan baik bagi siapa pun yang datang berkunjung.
Tak jauh dari pagoda, berdiri sebuah kelenteng tua bernama Hok Tjing Bio, yang sudah ada sejak 1962. Tempat ibadah ini masih aktif hingga sekarang, menjadi titik spiritual bagi umat Tionghoa yang datang untuk berdoa atau berziarah. Di halaman kelenteng, terdapat pula dua makam yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan Tan Bun An dan Siti Fatimah. Letaknya berdampingan, seolah memperkuat simbol cinta abadi antara dua budaya yang berbeda, yakni China dan Sriwijaya.
Di samping makam, terdapat sebuah pohon bernama ‘Pohon Cinta’ yang terinspirasi dari kisah cinta Siti Fatimah dan Tan Bun An. Masyarakat percaya pasangan yang mengukir nama di pohon ini akan diberkahi hubungan yang langgeng hingga pernikahan. Oleh karena itu, Pulau Kemaro sering disebut sebagai ‘Pulau Jodoh’. Hingga kini, banyak peziarah datang untuk berdoa, mengenang kisah Tan Bun An dan Siti Fatimah, atau sekadar meletakkan bunga sebagai bentuk penghormatan.
Migrasi, proses akulturasi, dan keharmonisan budayaKomunitas Tionghoa sudah ada di Palembang sejak abad ke-17. Para pedagang dari berbagai wilayah di China datang melalui jalur maritim membawa beragam barang dagangan, seperti keramik, sutra, dan rempah-rempah. Namun, selain perdagangan, mereka juga membawa tradisi dan budaya yang perlahan-lahan berbaur dengan masyarakat setempat. Banyak dari mereka memutuskan untuk menetap di Palembang, menikah dengan penduduk lokal, dan membentuk komunitas yang hidup berdampingan.
Dari sini, lahirlah pernikahan campuran yang menjadi jembatan sosial dan budaya antara kedua kelompok. Proses migrasi ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial dan budaya yang mendalam. Melalui interaksi sehari-hari dan pernikahan campuran, terjalin akulturasi kuat antara etnis Tionghoa dan penduduk lokal.
Akulturasi ini terasa dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari dapur rumah tangga hingga perayaan tahunan. Budaya Tionghoa melebur secara alami ke dalam tradisi lokal. Sebagai contoh, kuliner khas Palembang yang kaya rasa merupakan hasil perpaduan tradisi memasak Tionghoa dan Melayu. Hidangan populer seperti pempek, mi celor, dan kuah cuko menunjukkan sentuhan rasa peranakan yang unik.
Selain kuliner, bahasa, struktur keluarga, dan bahkan praktik keagamaan pun memperlihatkan pengaruh silang yang kuat antara kedua budaya.
Simbol harmoni antaretnis ini juga tercermin jelas dalam keberadaan Pulau Kemaro sebagai titik temu budaya. Pulau kecil di Sungai Musi ini bukan hanya merupakan lokasi bersejarah, melainkan lambang toleransi dan kehidupan multikultural yang telah berlangsung berabad-abad.
Masyarakat Tionghoa dan warga lokal Palembang hidup berdampingan secara damai, saling berbagi tradisi, dan menghormati satu sama lain. Sebagai contoh, perayaan Cap Go Meh di Pulau Kemaro tidak hanya menjadi milik komunitas Tionghoa, tapi juga melibatkan masyarakat luas sebagai bentuk penghargaan atas warisan budaya bersama.
Pulau Kemaro menjadi pusat perayaan Cap Go Meh yang digelar setiap tahun pada hari ke-15 setelah Imlek. Pada momen istimewa ini, ribuan pengunjung dari komunitas Tionghoa maupun masyarakat umum berkumpul di pulau kecil ini untuk merayakan tradisi yang sarat makna tersebut.
Acara dimulai dengan doa bersama di kelenteng sebagai bentuk penghormatan dan syukur, kemudian dilanjutkan dengan pelepasan lampion warna-warni yang terbang menghiasi langit malam, menciptakan pemandangan magis yang memukau setiap mata yang melihatnya. Tak ketinggalan, pertunjukan barongsai yang energik dan penuh semangat menambah kemeriahan suasana, sekaligus menjadi simbol keberanian dan keberuntungan.
Perayaan ini berhasil menggabungkan berbagai lapisan masyarakat dalam semangat toleransi dan saling menghormati, memperkuat identitas multikultural kota ini.
Viona (25), salah satu pengunjung yang berkesempatan merasakan langsung festival itu, membagikan pengalamannya dengan antusias. "Suasana Cap Go Meh di Pulau Kemaro sangat meriah dan penuh kehangatan. Selain menikmati keindahan pemandangan dan pertunjukan, saya juga bisa merasakan betul bagaimana budaya Tionghoa dan lokal Palembang menyatu harmonis di sini. Ini benar-benar destinasi yang wajib dikunjungi saat ke Palembang," katanya.
Antusiasme yang dirasakan Viona menunjukkan bahwa festival ini bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga pengalaman wisata yang memperkaya sekaligus memperkuat daya tarik Pulau Kemaro di mata wisatawan lokal maupun mancanegara sebagai simbol kebinekaan yang hidup di tengah masyarakat Palembang.
Pulau Kemaro sebagai destinasi wisataPulau Kemaro tidak hanya menjadi saksi sejarah dan simbol akulturasi, tetapi juga telah berkembang menjadi destinasi wisata budaya yang populer di Palembang. Pulau ini dibuka setiap hari, mulai pukul 08.00 pagi hingga 17.00 WIB, memberikan waktu yang cukup bagi para wisatawan untuk mengeksplorasi keindahan dan kekayaan budaya yang ada.
Untuk menuju Pulau Kemaro, pengunjung biasanya menyusuri Sungai Musi menggunakan perahu tradisional dari kawasan Benteng Kuto Besak atau Dermaga 16 Ilir dengan waktu tempuh sekitar 15-20 menit. Perjalanan singkat ini menawarkan pemandangan Sungai Musi yang memukau sekaligus menambah pengalaman berwisata yang unik.
Pulau Kemaro juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan sejarah. Pulau ini dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mengatur perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs-situs bersejarah di seluruh Indonesia.
Dengan status ini, setiap aktivitas di Pulau Kemaro diatur untuk memastikan keberlanjutan warisan budaya yang ada, sekaligus menjaga agar tidak terjadi kerusakan akibat kunjungan wisata yang terus meningkat.
Dengan kekuatan cerita legendaris, warisan budaya Tionghoa yang masih hidup, serta dukungan aktif dari pemerintah untuk pengembangan fasilitas wisata, Pulau Kemaro menunjukkan potensi besar sebagai ikon pariwisata budaya dan toleransi di Sumatra Selatan.
Ke depannya, perpaduan antara pelestarian nilai sejarah dan modernisasi infrastruktur diharapkan mampu menjadikan pulau ini tak hanya sebagai tempat berziarah atau berlibur, tetapi juga sebagai ruang perjumpaan antarbudaya yang menginspirasi.
Laporan: Redaksi



.jpg)